Menilik Kearifan Epos Ramayana
Judul Buku : Ramayana
Penulis : Wawan Susetya
Penerbit : Narasi, Yogyakarta
Cetakan : I, 2008
Tebal : xii + 228 halaman
Berawal dari kisah Ramayana, karya Walmiki seorang pujangga kenamaan India
yang kemudian mendarah-daging di Indonesia, khususnya bagi masyarakat Jawa. Sebagaimana
pula kisah dalam Mahabharata karya spektakuler Wiyasa, pujangga besar India. Kedua
epos ‘Ramayana’ dan ‘Mahabharata’ tersebut, sebagaimana dijelaskna Marwanto S.Kar
dan R.Budhi Moehanto-dalam bukunya ‘Apresiasi Wayang’-memiliki kelebihan karena
isinya bersifat universal menyangkut hidup dan kehidupan di dunia. Tak
berlebihan kiranya, jika dalam pandangan Agama Hindu, wiracarita ‘Ramayana’ dan
‘Mahabharata’ merupakan pedoman hidup (pepakem) yang berhubungan dengan
berbagai masalah kehidupan, seperti agama, filsafat, politik, kemasyarakatan, kepribadian,
keluarga, keperwiraan, keutamaan, dan seterusnya.
Kepopuleran kisah dalam ‘Ramayana’ maupun ‘Mahabharata’ di Jawa-khusunya-memang
sangat beralasan dan wajar. Pertama, masyarakat Jawa saat itu mayoritas memang
beragama Hindu dan Budha, sehingga mendukung memasyarakatnya kisah atau cerita
yang berasal dari India tersebut. Kedua, kiat memasukkan nilai-nilai keagamaan
ke dalam kisah atau cerita ‘Ramayana’ dan ‘Mahabharata’ terlihat memang sangat
efektif dan efisien.
Itulah sebabnya, ada peranan besar dari para pujangga Jawa-khususnya para
Wali Sanga-untuk ‘mengislamkan’ ke dua epos tersebut dan mempopulerkannya
kepada masyarakat pada awal proses Islamisasi di Jawa; yakni dipakai sebagai
sarana dakwah Islam kepada masyarakat Jawa.
Dalam buku ‘Bharatayuda’; Ajaran, simbolisasi, filosofi, dan maknanya bagi
kehidupan sehari-hari karya Wawan Susetya (2007), dijelaskan bahwa kedua epos
‘Ramayana’ dan ‘Mahabharata’ tak lepas dari nuansa melo-drama yang
bersinggungan dengan romantisme percintaan, nafsu kekuasaan dan menguasai, kepahlawanan
dan keberanian, perang, bergeloranya ego-syahwat keinginan dan sentimen-sentimen
pribadi, dan seterusnya sampai kejujuran dan kebohongan.
Bahkan, jika dilihat secara permukaan, cerita dalam pewayangan seolah-olah
hanya berkisah tentang kerajaan alias kekuasaan, harta (warisan) dan wanita; dikenal
dengan istilah ‘tiga ta’ (harta, tahta, dan wanita). Tak ayal, untuk
menggambarkan kedua epos tersebut diungkapkan dengan ‘jargon’; sadumuk bathuk
sanyari bumi dipun labeti pecahing dhadha wutahing ludira’,-seorang isteri dan
sejengkal tanah akan dibela hingga darah penghabisan.
Memang, sacara sepintas lalu, dalam buku berjudul ‘Brubuh Ngalenga’; Perang
Besar antara Wadya Raseksa dengan Bala Wanara. Ini seoalah-olah hanya
mengisahkan bahwa terjadinya perang besar antara Sri Rama Wijaya yang dibantu
bala wanara dengan Rahwana Raja yang dibantu wadya raseksa, karena untuk
merebut isteriya Dewi Shinta. Sehingga, seolah-olah kisa ‘Ramayana’ ini hanya
masalah rebutan seorang wanita. Sementara, dalam ‘Bharatayuda’ hanya rebutan
warisan tahta Ngastina, wajarlah jika berkembang unkapan pameo; ‘sadumuk bathuk
sanyari bumi dipun labeti pecahing dhadha wutahing ludira’-makna sadumuk bathuk
artinya isteri, sedang sanyari bumi berarti sejengkal tanah.
Padahal, sesungguhnya tak sesederhana itu, kehadiran buku ini, Ramayana; karya
Wawan Susetya, setidaknya ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Dalam
kisah Ramayana ini mengandung beberapa makna religius-spiritual yang dikemas
secara simbolis dan filosofis, diantaranya yakni: Pertama, mengandung
pralampita pati (melambangkan proses kematian); yakni seorang manusia yang akan
marak seba (menghadap) kepada Gusti Kang Akarya Jagad, sebagaimana juga
dinyatakan dalam ‘Serat Wedhapurwaka’-dalam S. Padmosoekotjo; ‘Silsilah Wayang
Purwa Mawa Barita’ Jilid III (1982).
Kedua, mengisyaratkan adanya Kamphala; Karma; penggawe (perbuatan), sedang
phala; woh (hasil). Dengan demikian, Karmaphala adalah ngundhuh wohing panggawe
(menuai hasil perbuatannya yang telah lalu). Dalam kontek ‘Ramayana’ misalnya, Prabu
Dasamuka yang dur angkara murka serta adingang-adingung-adiguna akhirnya
mendapatkan hukuman dari perbuatannya, yakni terkena anak panah ‘Kiai
Guwawijaya’ milik Sri Rama Wijaya. Bahkan, badannya dijepit gunung oleh Raden
Anoma hingga Rahwana Raja mengerang kesakitan. Akhirnya pula, roh-nya
gentayangan, karena ia mati tidak sempurna. Makanya dalam kisah ini, roh Prabu
Dasamuka yang masih gentayangan itu selalu menebarkan benih kejahatan melalui
kumara Rahwana Raja, disebut Kumara Godhayitma.
Ketiga, kisah ‘Ramayana’ sebenarnya merupakan simbolik perang antara
kebajikan atau kautaman (Sri Rama Wijaya) dengan kejahatan atau angkara murka
Rahwana Raja; Prabu Dasamuka. Jargon yang seringkali terdengar dalam masalah
ini, yakni ‘Suradira jayaningrat lebur dening pangastuti’-kejahatan atau
angkara murka akan lebur dikalahkan oleh kebajikan, atau dalam pameo lain; ‘Becik
ketitik ala ketara’ artinyal kebaikan dan keburukan akan terlihat di belakang
hari.
Keempat, mencerminkan metafor atau simbolik mengenai perang melawan hawa
nafsu dalam diri manusia. Dalam gambaran diri manusia, sebenarnya disimbolkan
Raden Wibisana; yakni simbol nafsu muthamiannah-jiwa yang tenang; anteng, jatmika-dalam
diri manusia. Oleh karena itu, Wibisana-simbol nafsu mutmainnah-maka ia harus
memerangi hawa nafsunya sendiri, yakni dengan memerangi saudara-saudaranya; Prabu
Dasamuka-lambang nafsu ammarah, Kumbakarna-lambang nafsu lawwamah, dan
Sarpakenaka-lambang nafsu supiyah; mulhimah, tentu, ia tidak bisa berdiri
sendiri dalam memerangi hawa nafsunya, tetapi harus bergabung dengan Sri Rama
Wijaya-lambang ‘pencer’-nya dari ‘sedulur papat lima pancer’.
Diantara kisah yang menarik dalam buku setebal 228 halaman ini, adalah
Wejangan ‘Ngilmu Hasthabrata’ Sri Rama Wijaya kepada dua orang Raja Binathara, yakni
kepada Prabu Bharata, putra Prabu Dasarata dengan Dewi Kekayi setelah
dinobatkan sebagai Raja Binathara di Negara Ayodya dan Raden Gunawan Wibisana
putra Begawan Wirsawa dengan Dewi Sukesi pada saat penobatan sebagai Raja
Binathara di Negara Singgelapura.
Wejangan ‘Ngilmu Hasthabrata’ Sri Rama Wijaya kepada dua orang saudaranya-yakni
kepada Prabu Bharata dan Prabu Gunawan Wibisana tersebut merupakan konsep
kepemimpinan sejati’; yakni meneladani delapan anasir alam sebagai lelaku
seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahan dan kepemimpian agar menjadi
pemimpin yang adil dan bijaksana. Yang jelas, buku ini sangat pantas untuk
disimak dan dikaji oleh semua kalangan masyarakat.
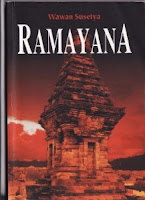
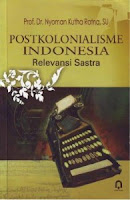

Komentar